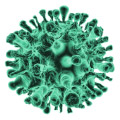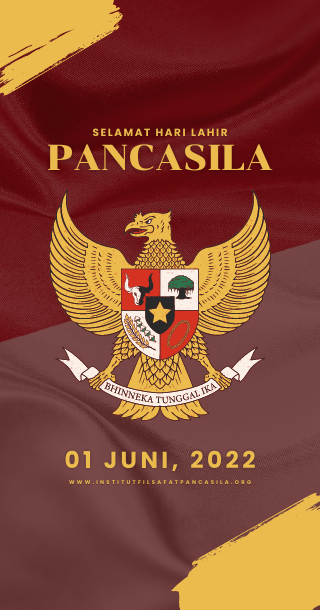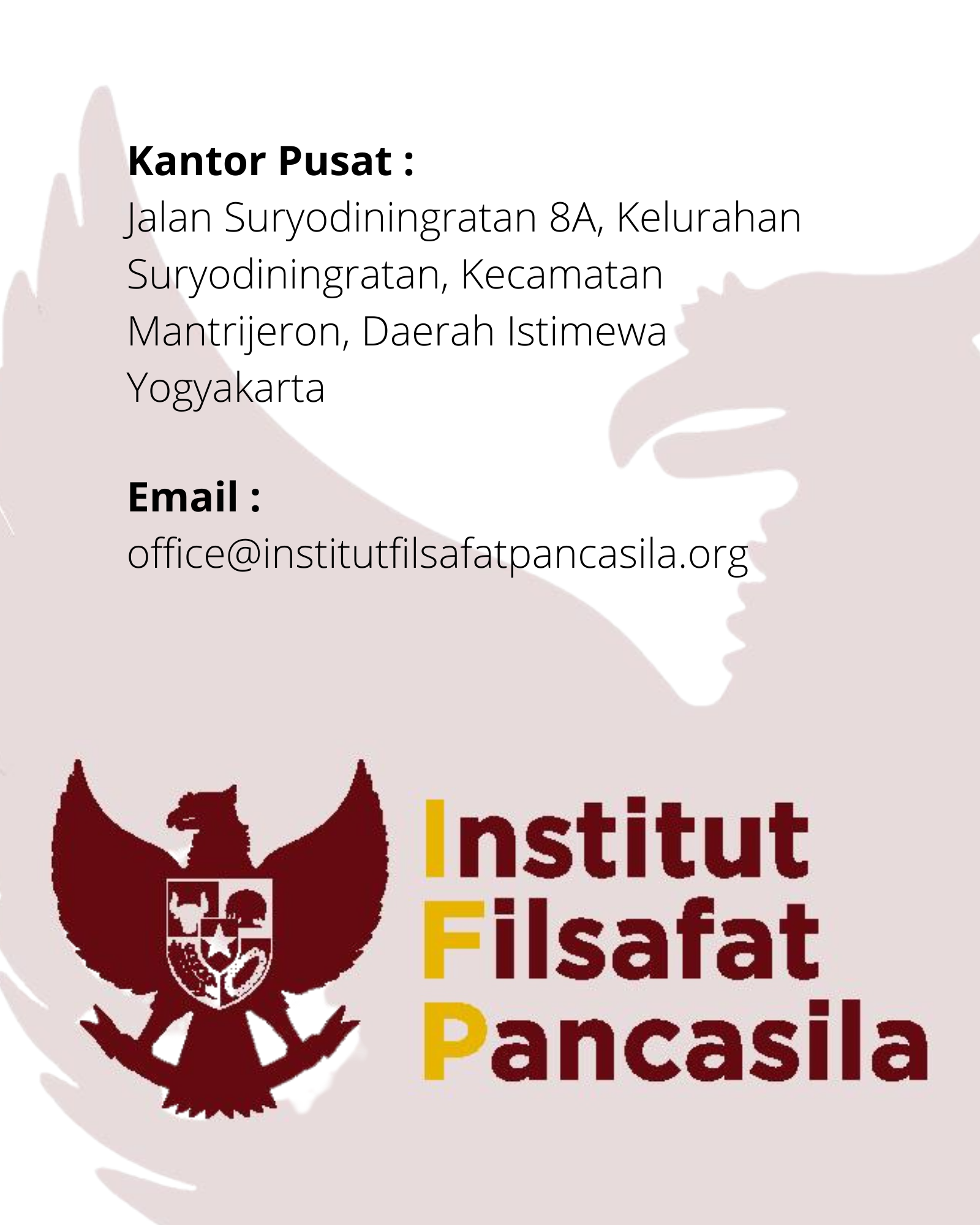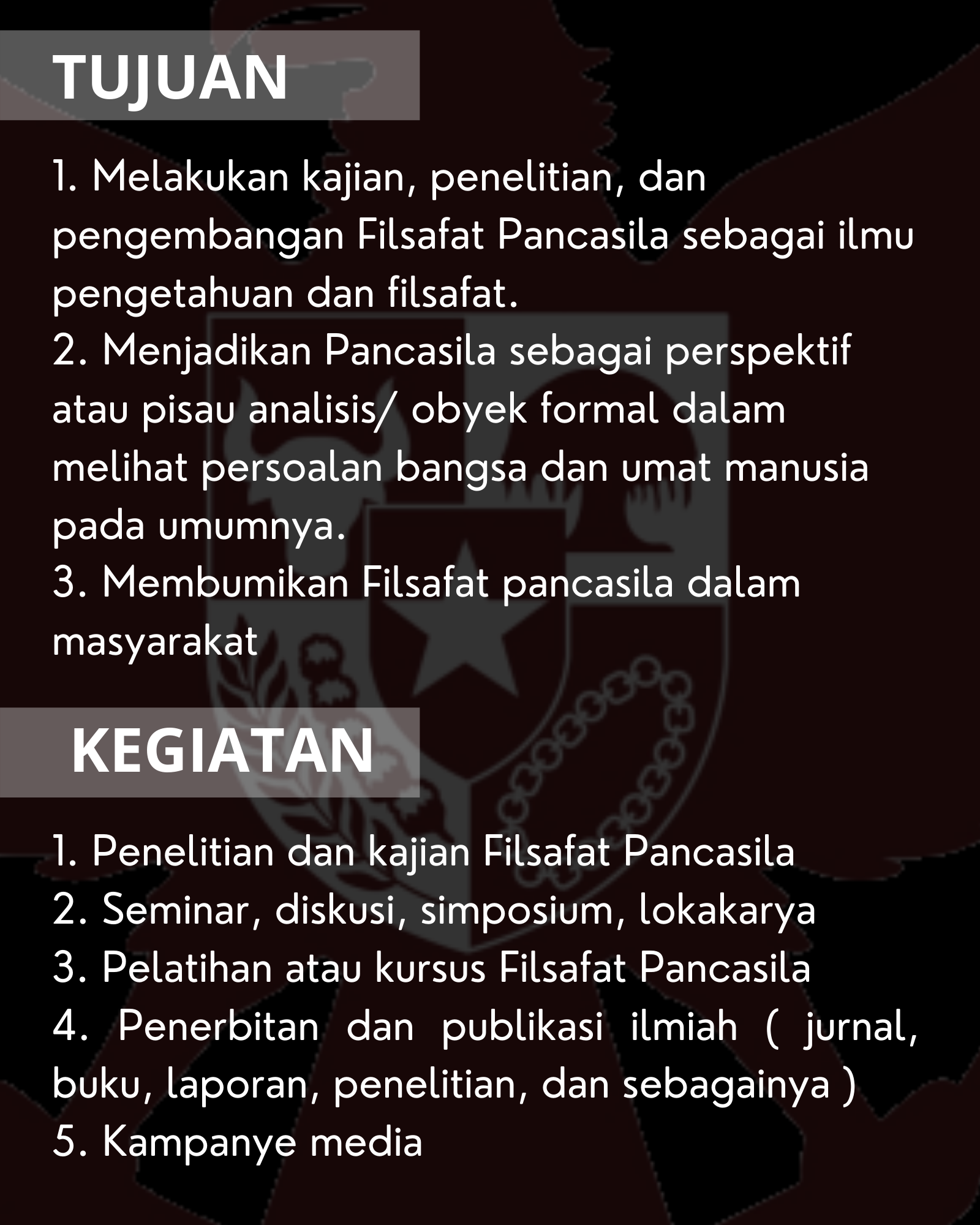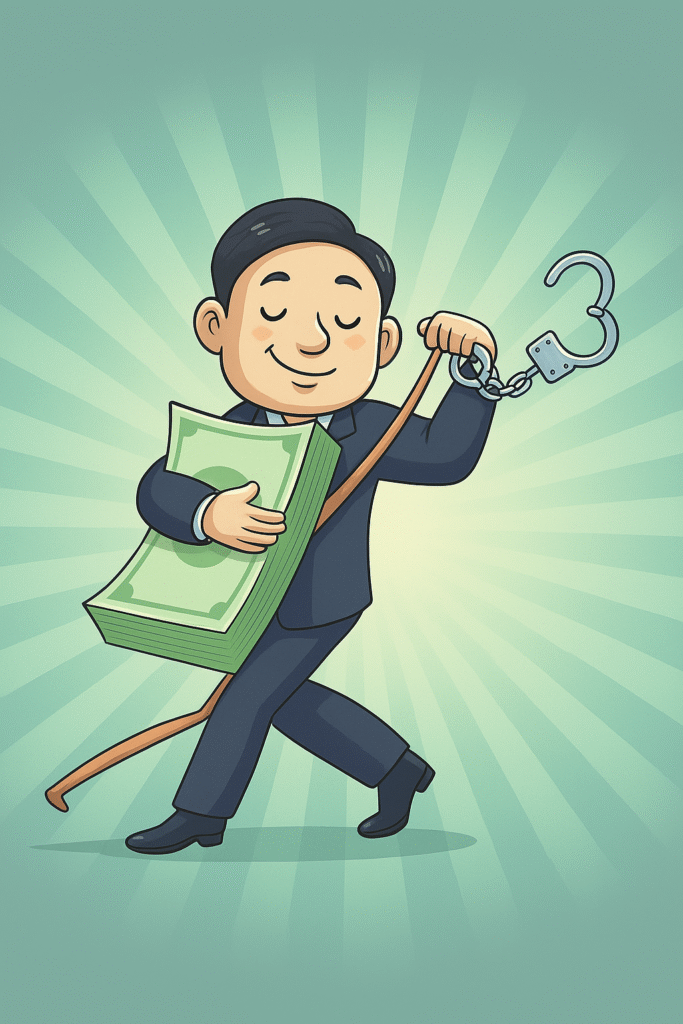
Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel kerap kali mondar mandir, inspeksi mendadak (sidak) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ia bermanuver tabola bale, seolah menaruh kepedulian pada para tenaga kerja, yang ijazahnya ditahan perusahaan. Mereka berharap penuh dengan kehadiran Noel. Berpakaian formal lengkap dengan beragam atribut, simbol pejabat kelas atas, lengkap dengan kacamata seakan intelek, Noel bergerak dengan embel-embel aktivis 98, dan menjadi mania(k) Jokowi. Ia seolah muncul menjadi politisi dalam garis memperjuangkan demokrasi di masa reformasi. Rupanya, ia serakah, tertangkap, dan menjadi tersangka suap. Buktinya, deretan mobil dan motor mewah memadati ambisinya. Kita tidak mudah meletakkan kepercayaan pada politisi dengan motif haus kekayaan melalui kekuasaan.
Di salah satu percakapan, ia percaya diri, bercuap: suap tidak akan melunturkan integritasnya. Lagi-lagi, cuap adalah cuap! Cuapannya menguap terbawa angin, dan berlalu begitu saja. Noel terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK, dengan dugaan pemerasan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Cuap-cuap integritas dengan bukti mondar-mandir sidak, ternyata ia adalah wujud politik tabola bale, sekedar mondar mandir, berputar-putar hingga terjungkir balik oleh kata dan tindakan dalam jebakan uang dan kekuasaan koruptif. Istilah terakhir inilah yang menjatuhkannya, hingga pada sumur durjana tanpa dasar.
Durjana Politik
Apa yang bisa kita telisik dari tertangkap dan menjadi tersangka suap dari Wamenaker ini? Bila kita menganggap itu hanyalah fenomena biasa bahwa dalam politik, perilaku koruptif dan kesenangan memperkaya diri menjadi wajar. Situasi tersebut kerap menyembul dalam gaung media sosial. Namun, simplifikasi tersebut, menandakan situasi gelap yaitu banalitas. Istilah terakhir ini membuat politik di Indonesia menjadi gelap, banal, licik, di mana kejahatan korupsi terlihat begitu transparan, tapi warganya hanya berkeluh kesah, dan kemudian mereda. Situasi yang terus melingkar, tabola bale dari politik kewargaan. Kita hanya diam, mengamini saat melihat para durjana menari bebas dalam mengeruk anggaran negara dalam wujud pemerasan, tantiem, sandera lawan politik dengan ancaman “dilaporkan ke KPK”, dan sebagainya, dan sejenisnya.
Presiden bercuap perangi korupsi di Sidang Tahunan. DPR asyik berjoget. Yang terjadi, cuapan tinggallah cuapan belaka. Presiden, DPR, dan Noel adalah cuapan-cuapan yang hampir tidak bisa dipercaya. Cuapan politik, bila tanpa disertai pengawasan, kontrol, dan integritas diri, maka menciptakan durjana politik. Ada pesimisme saat membaca, melihat, dan merasakan politik kekinian. Satu pertanyaan retrospektif, apa lagi yang bisa dipercaya dari cuap-cuap para durjana itu?
Satu hal yang menarik, yang bagi saya menjadi pintu untuk memahami durjana politik yang semakin mengganas, meranggas, dan bertindak dalam keliaran di semua dimensi kehidupan kewargaan Indonesia. Peristiwa itu tepat berada saat di Sidang Tahunan itu, para politisi berjoget-joget, dengan diputarnya lagu tabola bale. Menyebalkan! Joget-joget tersebut mengganggu kesadaran politik, bahwa ada yang jauh lebih mulia bahwa di depan mata korupsi merajalela. Kolusi tak bisa diredam, dan nepotisme hadir melahirkan anak haram konstitusi. Para politisi, berjoget, kita tanpa sadar juga ikut berjoget. Karena irama, mendendang, kita tanpa sadar masuk dalam pusaran politik tabola bale.
Dalam situasi ini, politik, bagi saya, adalah hubungan antar dunia yang saling berkaitan dengan adanya kepekaan pada situasi yang saat ini sedang sulit dan rumit. Dari sini, kita coba membaca politik tabola bale dengan bantuan seorang filsuf bernama Jacques Rancière. Ia menegaskan “Politics is not made up of power relationships; it is made up of relationships between worlds.”
Petikan kalimat Rancière ini menggelitik untuk menganalisis pada kasus banalitas di atas. Bagi sebagian warga, berita itu tak lagi menimbulkan keterkejutan, bahkan nyaris hambar. Seolah-olah drama korupsi pejabat adalah sinetron usang yang diputar ulang: tokohnya berganti, alurnya sama, ending-nya pun bisa ditebak. Fenomena kebosanan publik ini yang saya sebut sebagai politik tabola bale, politik mondar-mandir, maju-mundur, jungkir-balik, dan muter-muter tanpa arah. Politik yang seolah berisik dan penuh drama, tetapi ujungnya nihil transformasi. Kita menyaksikan korupsi, menyoraki di media sosial, lalu melupakannya dengan cepat. Sementara itu, para politisi tetap melenggang, sebagian bahkan tersenyum di depan kamera.
Politik Murahan dan Ketidakselarasan
Mengapa politik bisa terjerembab ke ruang murahan semacam ini? Karena nilai integritas, peradaban, dan intelektualitas yang seharusnya menopang politik, terkikis oleh logika transaksional. Politik berubah menjadi arena kalkulasi keuntungan, bukan lagi praksis memperjuangkan keadilan. Maka, korupsi yang semestinya menjadi aib, kini ditanggapi publik hanya dengan gumaman: “Ah, biasa saja.”
Rasa apatis ini lebih berbahaya daripada skandal korupsinya sendiri. Sebab, ketika warga sudah tidak percaya lagi pada kemungkinan politik yang bersih, maka politik akan kehilangan daya hidupnya. Politik tabola bale ibarat panggung sandiwara yang menampilkan kegaduhan tanpa substansi, dan kita, para penonton, tetap setia menyaksikan meski sudah bosan.
Di sinilah Jacques Rancière menawarkan cara pandang yang segar. Bagi filsuf asal Prancis ini, politik sejati bukanlah sekadar perebutan kekuasaan atau jabatan, melainkan tindakan yang mengganggu “pembagian yang sudah mapan” (distribution of the sensible). Politik muncul saat mereka yang dianggap tidak punya suara, tiba-tiba bersuara. Politik hadir saat ketidakselarasan menginterupsi keteraturan semu. Jika kita terapkan gagasan ini, maka skandal korupsi Noel bukan sekadar kasus hukum, melainkan cermin dari absennya “politik sejati” dalam ruang publik kita. Sebab, yang terjadi hanyalah reproduksi kekuasaan lama, dengan aktor baru yang mengulang pola serupa. Politik tidak benar-benar hadir, melainkan hanya “politik” meminjam istilah Rancière, yaitu tata kuasa yang sekadar mengatur siapa dapat apa, siapa duduk di mana, tanpa pernah benar-benar mengguncang status quo.
Dalam kacamata ini, warga yang pasrah, bosan, atau menganggap korupsi sebagai hal wajar, sejatinya sedang terjebak dalam logika kepolisian. Kita tidak lagi menuntut politik yang adil, melainkan hanya mengonsumsi berita politik sebagai hiburan. Politik menjadi tontonan, bukan percakapan tentang dunia yang lebih baik.
Membalik Politik Tabola Bale
Maka pertanyaan prospektifnya, apakah kita akan terus membiarkan politik tabola bale ini berulang? Apakah kita akan terus menonton tanpa ikut bersuara? Di titik inilah, Rancière memberi tantangan: politik sejati lahir ketika warga menjadi bagian tapi bukan bagian (the part with no part), dalam merebut ruang artikulasi. Artinya, kebosanan harus diolah menjadi perlawanan; ketidakpedulian harus diubah menjadi percakapan kritis. OTT KPK terhadap pejabat selevel wakil menteri mestinya bisa menjadi momen korektif, bukan sekadar gosip harian. Kita bisa menggunakannya sebagai pintu masuk untuk bertanya: mengapa partai politik masih lemah dalam rekrutmen kader berintegritas? Mengapa jabatan publik masih dilihat sebagai kesempatan ekonomi, bukan ruang pelayanan? Mengapa kita, warga, cepat melupakan kasus korupsi tanpa menuntut akuntabilitas yang lebih keras?
Rancière mengingatkan bahwa politik adalah perjumpaan antar-dunia, antara yang didengar dan yang disenyapkan, antara yang tampak dan yang disembunyikan. Jika kita terus membiarkan politik dikuasai segelintir elite dengan mental tabola bale, maka politik akan semakin jauh dari ruang bersama. Sebaliknya, jika warga mau menolak kebiasaan “ah, biasa saja,” dan mulai menyuarakan ketidakpuasan secara berkelanjutan, maka kita sedang mempraktikkan politik dalam makna sejati: membongkar keteraturan semu, menuntut dunia yang lebih adil.
Kasus Noel hanyalah satu episode dari serial panjang korupsi di republik ini. Tetapi ia bisa menjadi titik balik jika kita, warga, mau keluar dari jebakan politik tabola bale. Korupsi tidak boleh dianggap biasa; ia harus diperlakukan sebagai luka peradaban. Perubahan politik tidak dipahami hanya sekedar seperti lirik lagu tabola bale, dari rambu kepang dua, sekarang rambu merah-merah. Tetapi, dari ingatan pada pemikiran Rancière bahwa politik bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi tentang dunia macam apa yang kita ciptakan bersama. Maka pertanyaannya sederhana namun mendesak: apakah kita akan terus membiarkan politik sebagai tontonan murahan yang banal? Atau, kita berani menjadikannya ruang perjuangan demi integritas, peradaban, dan intelektualitas?