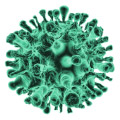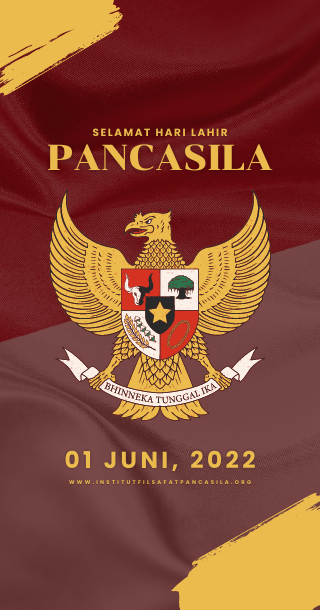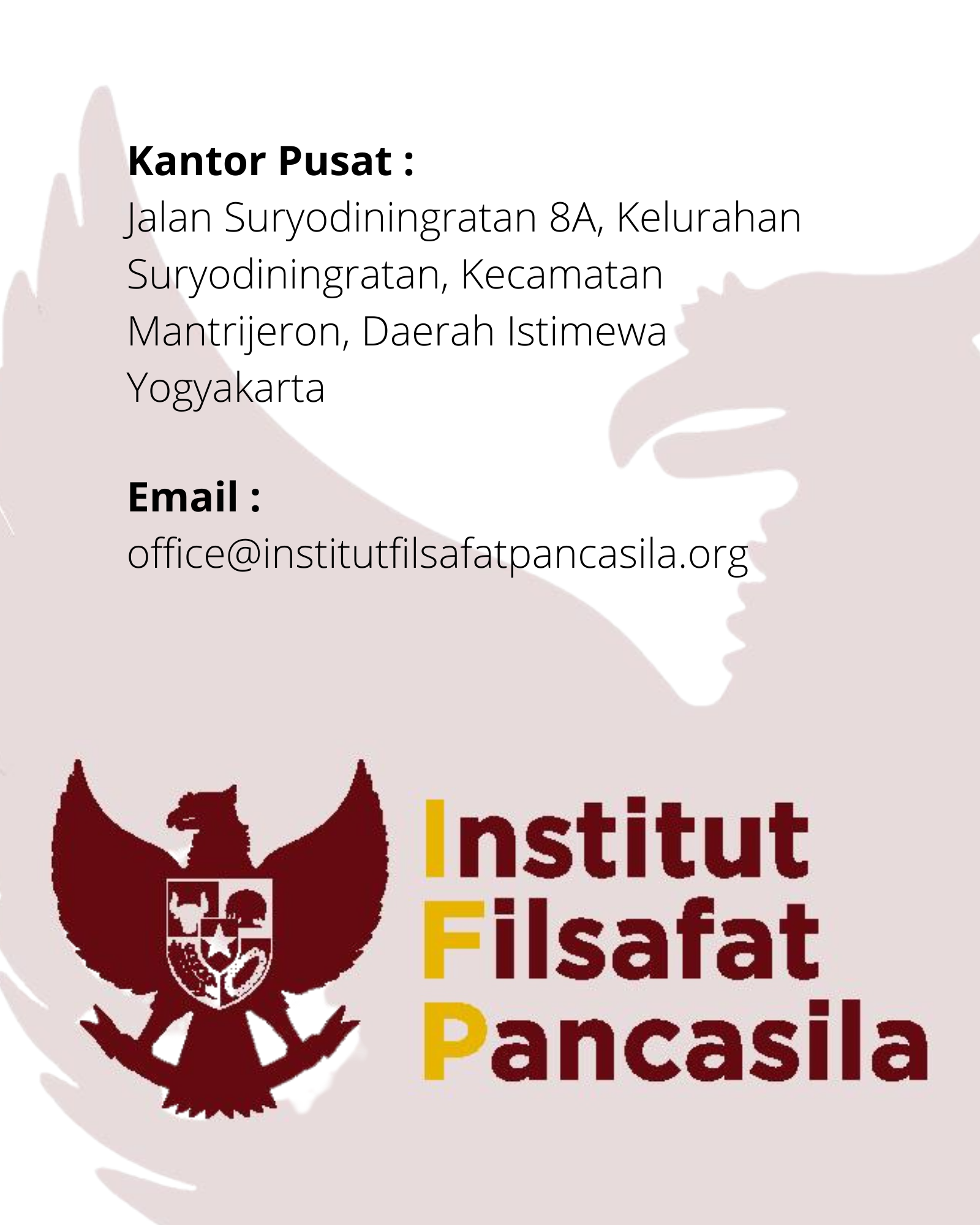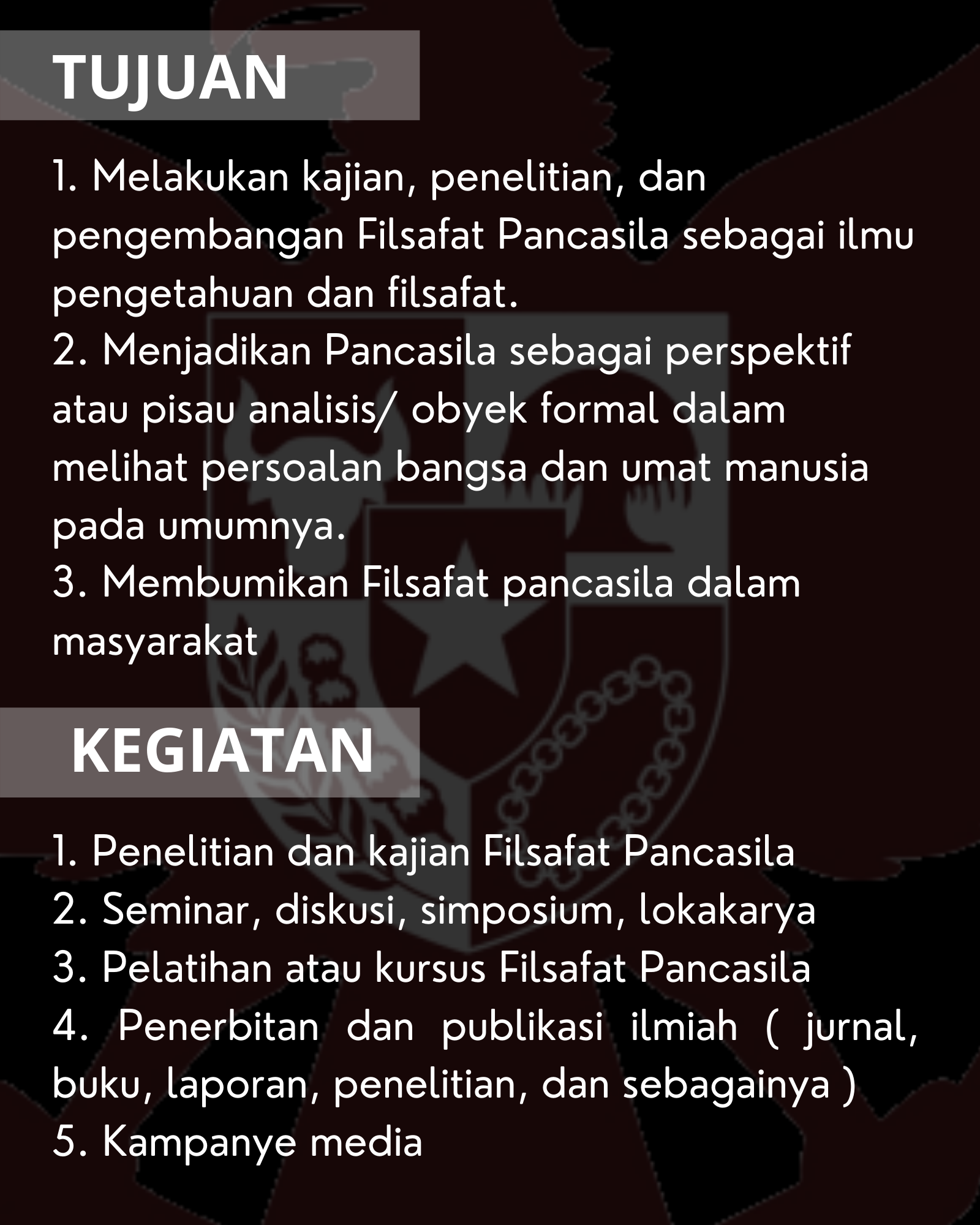Sejarah kejayaan Majapahit, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah lahir dari kejayaan dan peradaban yang besar. Sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah nusantara, dengan luas wilayah mencakup wilayah Indonesia saat ini, ditambah dengan sebagian Malaysia atau Semenanjung Melayu (Semenanjung Tanah Melayu: Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai), dan masa hidup yang panjang (kurang lebih 2 abad (berdiri sekitar 1293-1500 M), Majapahit karenanya memberikan pengaruh yang tidak sedikit bagi Bangsa Indonesia kontemporer. Pengaruh itu terutama dari masa kejayaan Majapahit selama pemerintahan Hayam Wuruk dengan mahapatih Gadjah Mada (1350 hingga 1389). Beberapa pengaruh besar itu dalam konteks Indonesia kontemporer dapat disebutkan diantaranya sebagai berikut.
Pertama, imajinasi negara kesatuan Republik Indonesia yang merentang dari Sabang Hingga Merauke. Konsep kesatuan ini yang meliputi seluruh wilayah nusantara tak pelak diinspirasi oleh sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gadjah Mada. Bahkan, jika dilihat dalam keseluruhan perdebatan mengenai usaha menentukan wilayah Indonesia selama awal-awal perjuangan kemerdekaan, wilayah Majapahit itulah yang menjadi salah satu referensi penting para pendiri bangsa. Dengan kata lain, selain wilayah jajahan Belanda sebagai batas penentuan wilayah, Majapahit juga menjadi bagian dari rujukan yang diperdebatkan dalam sejarah Indonesia ketika menentukan batas wilayah.
Kedua, desentralisasi pemerintahan. Kerajaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gadjah Mada memang bersifat ekspansionis sebagaimana ambisi mahapatih Gadjah Mada dalam sumpah Amukti Palapa. Namun, sifat ekspansionis itu tidak dilakukan melalui penggunaan kekerasan yang dilakukan secara brutal. Sebaliknya, penggunaan kekerasan dilakukan secara terukur. Dalam hal ini, Gadjah Mada meyakini bahwa penggunaan kekerasan tetap diperlukan sejauh hal itu dilakukan secara terukur.[1] Satu-satunya penggunaan kekerasan yang berakibat fatal barangkali adalah Perang Bubat. Disebutkan bahwa perang ini terjadi karena ambisi Gadjah Mada untuk menaklukan kerajaan Sunda Padjajaran. Namun, hal itu pula yang kemudian menjadi awal bagi kemunduran Gadjah Mada.
Dalam menjaga pemerintahan yang baik, Majapahit memberikan otonomi kepada kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya.[2] Sebagai simbol bahwa mereka tunduk pada Majapahit, setiap tahun memberikan upeti dan pada peristiwa-peristiwa tertentu datang ke pusat pemerintahan di Majapahit. Sebagai kompensasinya, Majapahit memberikan perlindungan terhadap negara di bawahnya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak tunduk atau melakukan pemberontakan akan dihancurkan seketika. Sebagaimana diketahui, Majapahit mempunyai armada laut yang sangat besar sebagai simbol kekuatan maritimnya. Saat itu, penguasaan laut menjadi kunci bagi kebesaran suatu kerajaan, dan Majapahit mampu menunjukkan hal itu. Dalam usahanya menjaga laut, Majapahit mempunyai ribuan kapal laut yang dilengkapi dengan meriam Jawa.[3] Baik konsep otonomi daerah dan juga strategi maritim kiranya menginspirasi Indonesia hingga saat ini.
Ketiga, semboyan Bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, diambil dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab itu ditulis di masa Majapahit. Bhineka Tunggal Ika merefleksikan kondisi kerajaan yang sangat menghargai keberagaman, terutama dalam hal agama. Pada masa kejayaan Majapahit, kehidupan beragam dijamin dengan sangat baik.
Di Majapahit terdapat multi-agama, dan yang terbanyak penganutnya adalah agama Siwa dari aliran Siwa Siddhanta dan agama Buddha Mahayana. Walaupun raja-raja Majapahit, kecuali ratu Tribhuwanatunggadewi, beragama Siwa, tapi mereka mengangkat pejabat-pejabat tinggi baik dari agama Siwa maupun Buddha.[4] Menurut kakawin Nāgarakertagama, di Majapahit, terdapat 4 agamawan (caturdwija), yaitu ŗsi-saiwa-sogatamahābrahmana, yang akan ikut melaksanakan ritual keagamaan. Resi (ŗsi) adalah pertapa, Saiwa adalah pendeta Siwa, Sogata pendeta Buddha dan Mahābrahmana adalah pendeta Hindu yang berasal dari luar Indonesia, antara lain dari India. Meskipun yang belakangan kadang kala tidak disebutkan sehingga hanya ada tiga agama, disebut tripaksa, yaitu ŗsi-saiwa-sogata.[5]
Inspirasi Majapahit dan Negara Pancasila
Sebagai negara besar dengan kebudayaan tinggi, Majapahit bukan hanya memberikan suatu rasa percaya diri bagi Bangsa Indonesia, tapi juga inspirasi bagi penyelenggaraan suatu negara-bangsa yang bersifat multietnis. Inspirasi itu mencakup bukan hanya bidang maritim, tapi juga diplomasi, pertahanan keamanan, pemerintahan, dan yang lebih penting sendi-sendiri keberagaman (agama, suku, dan budaya). Pancasila yang muatan utamanya adalah gotong royong[6] ataupun Bhineka Tunggal Ika[7] kiranya mefleksikan semangat Majapahit itu. Dalam Pancasila itulah, terkandung falsafah, dasar, dan ideologi negara yang menyangkut bagaimana negara bangsa seharusnya dikelola.
Negara Pancasila adalah negara yang mendasarkan pada sila-sila Pancasila di mana pengamalannya hanya mungkin jika setiap penyelenggara negara dan masyarakatnya memahami dengan baik setiap sila-silanya.
Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia hendak dihayati dalam kehidupan bangsa sebagai dasar bagi berkembang-suburnya Indonesia sebagai satu bangsa. Pancasila merupakan pernyataan “jati diri” bangsa (Hadi, 1994: 45). “Jati diri” merujuk pada kesatuan yang utuh dan seimbang dari suatu masyarakat atau manusia. Jati diri ini merangkum tiga aspek, yakni sebagai cerminan kepribadian, sebagai ungkapan identitas diri, dan keunikan masyarakat Indonesia. Sebagai rumusan kepribadian, pada satu pihak, kepribadian adalah penghayatan masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan di pihak lain kepribadian inilah yang dijadikan pedoman kehidupan bersama agar ditaati dan dikembangkan secara optimal (Hadi, 1994: 68).
Pancasila tidak hanya digali dari masa lampau yang dijadikan kepribadian pada waktu itu, tapi juga diidealkan sebagai kepribadian Bangsa Indonesia sepanjang masa. Hardono Hadi (1994: 69) menegaskan “unsur dasar yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa dari saat ke saat sepanjang hidup inilah yang disebut identitas diri bangsa Indonesia.” Selanjutnya, ketika Pancasila menjadi ciri khas maka pada waktu bersamaan menjadi keunikan bangsa Indonesia yang membedakan dirinya dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional.
Muatan pokok atau inti filsafat Pancasila adalah Bhineka Tunggal Ika. Kebhinekaan ini adalah wujud kerinduan akan kesatuan bangsa Indonesia dalam pengalaman kepelbagaian, yang sekaligus merupakan kerinduan seluruh umat manusia secara universal (Hadi, 1994: 112). Sebagai inti atau pokok dalam filsafat Pancasila, Bhineka Tunggal Ika memancar dalam keseluruhan sila-sila Pancasila. Kebhinekaan itu terpancar dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, kebebasan dalam hal agama dan kepercayaan, serta dalam pelaksanaan penghayatannya mendapatkan tempat yang istimewa dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Hadi, 1994: 112). Demikian juga kebhinekaan terpancar dalam sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Pancasila dalam Konteks Demokrasi Deliberatif (musyawarah-mufakat)
Teori demokrasi deliberatif dikemukakan oleh Filsuf Jerman, Jurgen Habermas, yang menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum dalam proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural (Hardiman, 2009a: 126). Dalam ruang publik itulah, kontrol rakyat bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, dalam kondisi-kondisi masyarakat kompleks maka pemerintahan oleh rakyat seyogianya dipahami sebagai kontrol atas pemerintahan secara tidak langsung melalui kekuasaan opini publik (Hardiman, 2009a: 128). Opini publik karenanya memegang peran yang sangat penting. Namun, opini publik ini tidak selalu harus dimaknai sebagai suara mayoritas. Sebaliknya, yang lebih penting-sesuai prinsip prosedural- adalah memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat mematuhi opini-opini itu. Dengan demikian, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. Dalam proses pembentukan opini inilah, seluruh gagasan atau opini yang saling “beradu” dan mengajukan klaim atas argumentasi-argumentasi rasional. Dari sini, diskursus akan terjadi dan akhirnya memunculkan suatu konsensus yang ditaati bersama segenap warga masyarakat.
Implementasi demokrasi diliberatif ini dalam konteks Indonesia adalah sila keempat Pancasila, yakni “Rakyat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan)”. Dalam pandangan Notonagoro, hakikat sila keempat ini dapat disarikan sebagai berikut.
- Arti yang terkandung dalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, bahwa Negara dan segala sesuatu keadaan dan sifat daripada negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat jadi lebih luas daripada pengertian demokrasi.
- Pengertian demokrasi terikat pada pengertian permusyawaratan/ perwakilan dan diambil dalam cita-cita kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang diselenggakan dalam permusyawaratan/perwakilan. Adapun cita-cita demokrasi politik adalah syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan
- Dalam kerakyatan terkandung pula demokrasi ekonomi
- Demokrasi politik adalah dalam rangka meraih maksud persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi. Demokrasi demi meraih kesejahteraan ekonomi, dengan demokrasi politik sebagai syaratnya.
- Dalam sila keempat, terkandung sila kelima.
Mengenai dasar politik negara berkedaulatan rakyat, Notonagoro menyatakan bahwa:
- Merupakan penjelmaan sila keempat baik dari unsur kerakyatan maupun permusyawaratan/perwakilan sebagai cita-cita politik
- Sila keempat tidak boleh disamakan dengan demokrasi karena kerakyatan adalah lebih luas kedudukannya daripada demokrasi politik
- Sila keempat merupakan penjelmaan pula daripada sila kelima.
Notonagoro lebih lanjut menyatakan bahwa sila kerakyatan memberikan makna bahwa kondisi negara bangsa harus sesuai dengan hakikat rakyat. Negara pada dasarnya kumpulan atau jumlah keseluruhan orang-orang Indonesia, yang jika ditarik ke dasarnya adalah manusia Indonesia. Oleh karena itu, negara kita dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Jika hal ini dikembalikan pada hakikat negara, maka negara Pancasila adalah negara dwi tunggal, negara monodualis, yang secara hakikat adalah negara yang memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan perseorangan dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, negara monodualis adalah “negara yang mencakup seluruh warganya atau seluruh rakyatnya, dengan lain perkataan adalah negara kerakyatan dan oleh karena itu bersifat demokrasi serta demokrasinya tidak dapat lain daripada demokrasi monodualis, yang mencakup pula seluruh rakyat.” Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa sila keempat sebenarnya jauh melampaui demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif, demokrasi sebatas dipahami semata ‘proses pengambilan keputusan’ atau ‘formasi opini publik’rasional, sedangkan sila keempat tidak hanya proses pengambilan keputusan atas dasar musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan, tapi juga cita-cita keadilan sosial dan ekonomi.
Penutup
Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah bangsa besar yang direpresentasikan dari keberadaan kerajaan Majapahit, yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini. Di era sekarang, tantangan terbesar Indonesia adalah mengelola bangsa yang beragam sambil melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik hingga mencapai taraf maju dan ‘hegemonik’ sebagaimana ditunjukkan oleh Majapahit. Dalam konteks implementasi Pancasila, sangat penting dan mendasar. Utamanya, dalam mengelola keragaman dan demokrasi, sebagaimana telah ditunjukkan oleh kerajaan Majapahit pada abad 13.
REFERENSI
[1] Yusak Farchan dan Firdaus Syam, Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, VOL. 11 No. 01. 2015
[2] Purwadi, Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit, Jurnal Konstitusi, VOLUME 3, NOMOR 4, DESEMBER 2006
[3] Sartika Intaning Pradhani, Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini, Lembaran Sejarah, Volume 13 Number 2 October 2017.
[4] Hariani Santiko, Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa: Perspektif Arkeologi, SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013
[5] Ibid.
[6] Agustinus W Dewantara (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Yogyakarta: Kanisius
[7] P Hardono Hadi (1994). Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisius